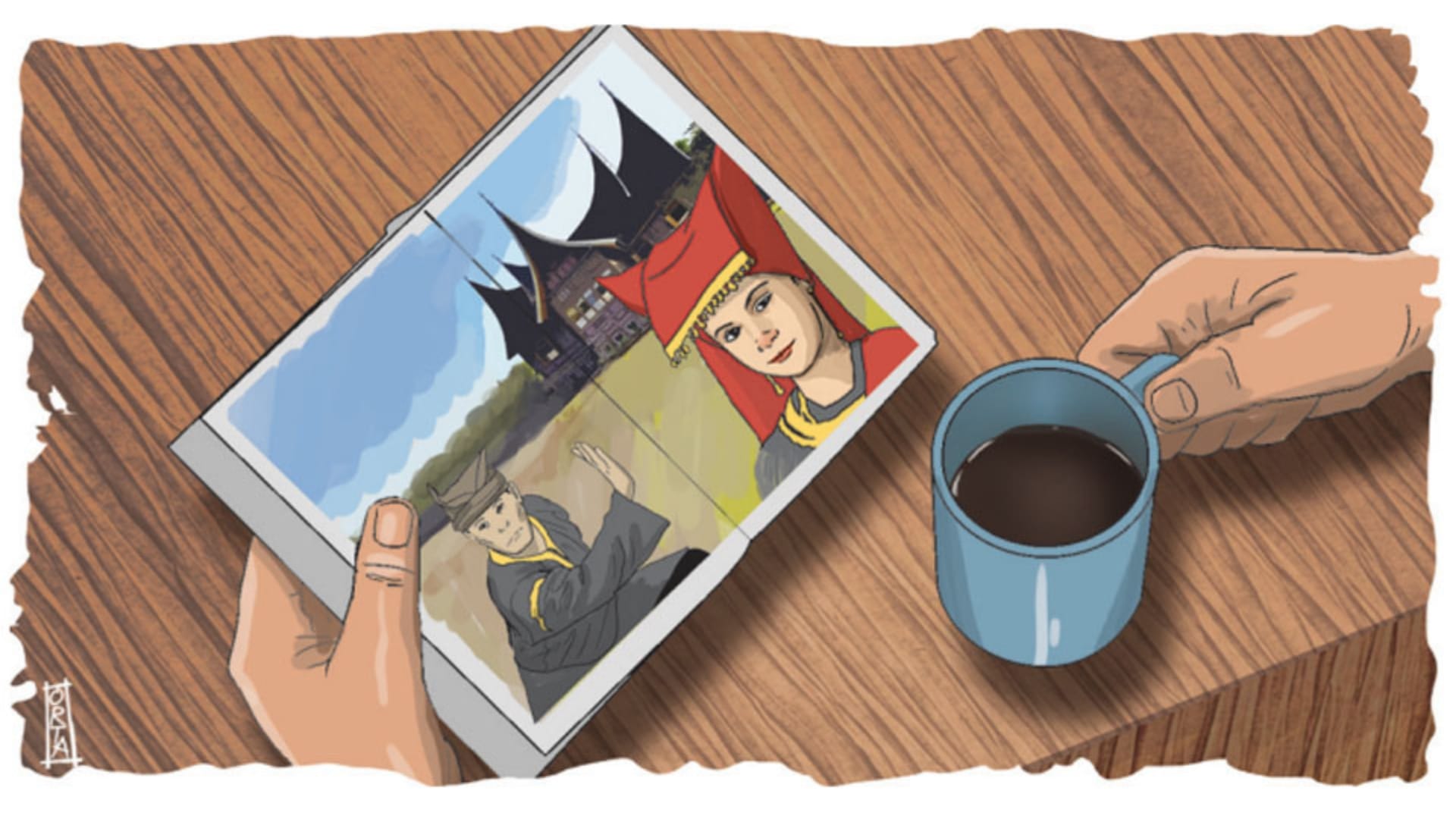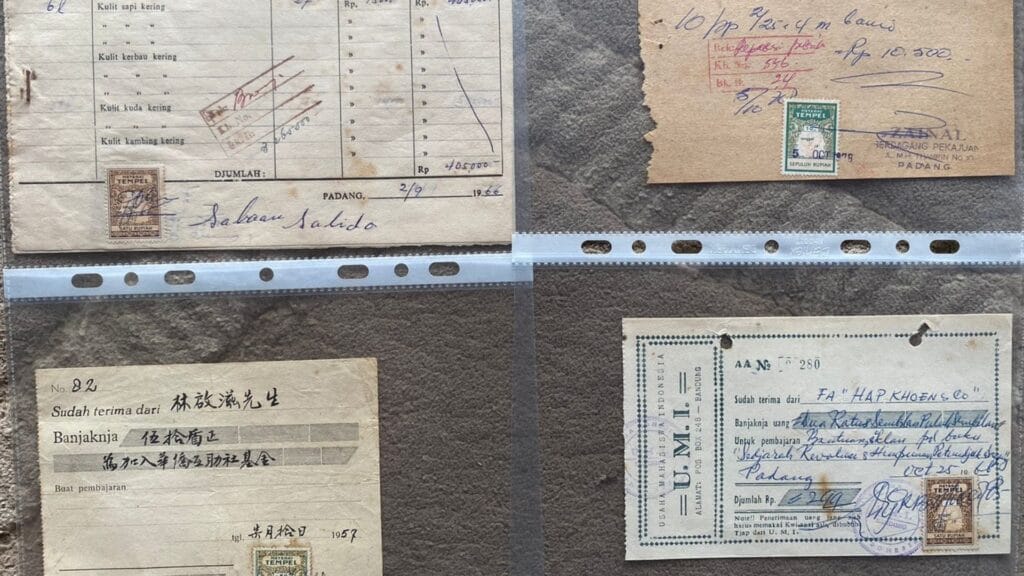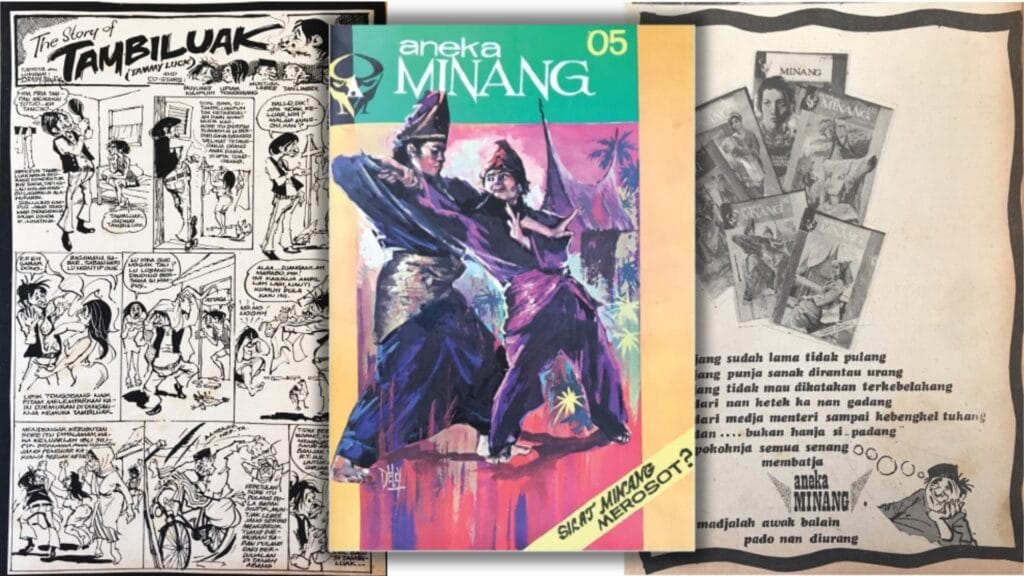Dalam kaba Rancak di Labuah dan Anggun nan Tongga, tuturan seorang ibu berpotensi mengandung banyak gaya bahasa yang berorientasi pada kearifan lokal. Gaya bahasa dimanfaatkan sebagai sarana estetis untuk menyampaikan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Gaya bahasa lokalitas dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran, petuah, nilai-nilai pendidikan untuk kematangan berpikir dan berbahasa seorang anak.
Diksi dan gaya bahasa lokalitas yang direpresentasi oleh seorang ibu dalam kedua kaba tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kematangan emosional dan bahasa anak. Kaba juga merupakan sarana yang tepat untuk menge- nalkan kembali kepada anak terhadap bahasa lokal dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai kearifan lokal. Diksi dan gaya bahasa dimanfaatkan untuk mewakili gagasan terhadap watak, perilaku, ajaran, anggapan atau stereotipe terhadap sesuatu hal. Misalnya, penggunaan nama tokoh dan tempat cerita yang digunakan sebagai alusio telah mencerminkan sisisosioantropologis yang mengacu kepada unsur lokalitas.
Gaya bahasa majas lokalitas Minangkabau dalam kaba Rancak di Labuah karya Dt. Panduko Alam dan Anggun nan Tongga karya Ambas Mahkota telah merefleksikan cara dan bentuk pendayagunaan bahasa ibu di Minangkabau. Secara setempat, melalui pengarang, bahasa seorang ibu dapat memengaruhi sikap dan cara pandang anak yang sedang mencari jati dirinya.
Dengan gaya perbandingan dan sindiran, ibu tidak serta merta menyampaikan maksud dan tujuan pembicaraan. Ibu dapat menggunakan majas perbandingan atau sindiran agar memperhalus kesan yang ditimbulkan dari segi nilai rasa terhadap bahasa.
Dari penggunaan gaya semacam itu, kehalusan dan ketegasan bahasa seorang ibu ketika mendidik anaknya merefleksi bahasa ibu yang ideal. Dengan demikian, bahasa seorang ibu di Minangkabau jelas memiliki nilai dan berfungsi didaktis. Pemilihan bahasa seorang ibu yang ideal ketika mendidik anaknya merupakan salah satu pengejawantahan dari nilai dan peran ibu di Minangkabau.
Pada tataran objektif, bahasa didayagunakan melalui pertimbangan yang matang dan mencerminkan bahasa sastra lisan. Di samping berfungsi didaktis, pilihan kata dan maknanya membentuk gaya yang ditemukan telah berfungsi estetis. Penggalian makna pada gaya bahasa yang bersifat tidak langsung membutuhkan daya analisis kritis terhadap maksud dan cara penyampaian. Pilihan kata dari bahasa tersebut berasal dari simbol-simbol yang mencerminkan ciri setempat.
Kemudian, pada gaya bahasa bermakna tidak langsung, memperlihatkan akar tradisi bahwa bahasa di dalam kaba didayagunakan dengan permainan bunyi, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Permainan kata kedua pengarang menunjukkan identitas bahasa, masyarakat, dan budaya Minangkabau yang sarat dengan gaya perbandingan dan sindiran.
Perbandingan dan sindiran dimanfaatkan agar kesan yang ditimbulkan dari tuturan ibu tidak mengandung kesalahpahaman dan dapat meningkatkan nilai rasa atau kepekaan anak dalam menerima bahasa. Identitas bahasa merujuk kepada cara penyampaian dan pendayagunaan diksi yang bersifat setempat sehingga menjadi identitas kebudayaan suatu masyarakat melalui gaya bahasa lokalitas Minangkabau. Setelah mengenal dan memahami cara dan bentuk pendayagunaan gaya bahasa, pembaca dapat merefleksikan bahasa seorang ibu yang ideal dalam hal menunjuk ajarkan anak- anaknya.
Gaya yang digunakan bersifat relatif tergantung kepada maksud dan tujuan gagasan yang disampaikan. Ketika gagasan yang dimaksud urgen dan esensial, orang Minangkabau dapat memanfaatkan gaya dan cara tidak langsung atau majas. Dengan sindiran, anak akan cepat mendapatkan efek terhadap gagasan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh ibu sebab demikianlah gaya dan cara merasa orang di Minangkabau umumnya.
Hal ini sejalan dengan pendapat Knight (2004: 14) yang mengatakan bahwa sindiran merupakan cara yang tepat digunakan untuk untuk menyesuaikan perspektif atau mengubah sikap dan perbuatan seseorang melalui lensa metafora sebagai mode definisi alternatif. Dalam hal yang bersifat linguistik, sindiran berfungsi melalui instansiasistilistik pada wacana, dimulai tataran sintaksis, semantis hingga pragmatis, yang juga dimediasi secara intersemiotik (Simpson, 2003: 8).
Gaya bahasa majas lokalitas yang direpresentasi oleh tokoh sebagai cerminan masyarakat dan budayanya menunjukkan bahwa cara dan bentuk pendayagunaan bahasa seorang ibu dapat mempengaruhi dan efektif untuk mengubah sikap dan perilaku anak. Di Minangkabau, dalam kaba Rancak di Labuah karya Dt. Panduko Alam dan Anggun nan Tongga karya Ambas Mahkota, direfleksikan bahwa dengan perbandingan dan sindirian anak sudah dapat mengerti maksud dan tujuan tuturan seorang ibu. Oleh sebab itu, sensitivitas anak terhadap bahasa dan maknanya mestinya sudah harus dimulai sejak ia kecil agar ia perlahan-lahan mengenal dan memahami rasa dan periksa (raso jo pareso).
Disamping itu, dalam kedua kaba tersebut, menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau sangat sarat dengan gaya bahasa tidak langsung (majas), tidak terkecuali gaya penegasan dan pertentangan (retorik). Dengan demikian, gaya bahasa bermakna langsung dan tidak langsung digunakan untuk memperindah dan memperhalus bahasa di samping juga untuk memperkuat efek gagasan terhadap lawan bicaranya.
Seorang Ibu di Minangkabau idealnya mampu mempertimbangkan diksi dan gaya bahasa sehingga nilai rasa yang diterima anak tidak hasil yang buruk dan tidak pula berdampak kepada psikologinya dalam hal berbahasa ketika sudah beranjak dewasa. Kepekaan dan kemampuan seorang anak, khususnya dalam berbahasa, sangat tergantung kepada cara berbahasa seorang ibu yang diterimanya sejak ia kecil. Pemerolehan itulah yang kadang kurang disadari oleh sebagian ibu, baik ibu sebagai orangtua kandung maupun sebagai pendidik, untuk mempertimbangkan aspek bahasa,yakni dari diksi dan bentuk (gaya bahasa).
Alusio Lokalitas Minangkabau
Dangakan pulo lai nak kanduang, sajauah-jauah bajalan, sabarek-barek manjunjuang, labo rugi kana juo, rasa nan jan dielakkan, tapi samantangpun bak nantun, lobo jo tamak jan dipakai, di dalam suko kajilah duko, dalam mulia kanalah hino, awak pangulu janyo urang.
(Dengarkan pula anak kandungku, sejauh-jauh berjalan, seberat-berat menjunjung, laba rugi ingat juga, rasa yang jangan dielakkan, tapi meskipun demikian, lobo dan tamak jangan dipakai, di dalam suka kajilah duka, dalam mulia ingatlah hina, kita penghulu bagi or- ang).
(Data 32/RdL/AUMP, Hlm. 57 Prg. 1)
Kata-kata yang bercetak tebal pada kutipan tersebut mengandung majas alusio lokalitas Minangkabau. Alusio lokalitas Minangkabau berusaha menyugestikan kesamaan antar orang, tempat, peristiwa atau suatu hal yang referensinya itu secara eksplisit mengacu terhadap objek yang sama-sama sudah dipahami oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dicermati pada kata-kata sajauah- jauah bajalan yang mengacu kepada perjalanan hidup; sabarek-barek manjunjuang mengacu kepada beban atau masalah yang akan dihadapi, labo rugi mengacu kepada konsekuensi yang akan ditanggungkan.
Dengan demikian, Rancak di Labuah dibekali oleh ibunya dengan ajaran atau nasihat berupa kata-kata yang bermakna seorang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika menempuh pengalaman atau hal yang akan dialami. Ajaran itu seyogianya memiliki muatan nilai-nilai ideal yang harus dimiliki oleh seorang ibu dan diturunkan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, relasi matrilineal di Minangkabau sangat kuat pengaruhnya karena peran ibu begitu besar terhadap perkembangan emosional anak-anaknya. Di banding posisi ayah, ibu memiliki waktu lebih baik berkomunikasi dengan anak-anaknya.
Satire Lokalitas Minangkabau
Kalau nak sanang hati Buyuang, cubolah bajalan hilia mudiak, jan takuik babareh baka, walaupun jauah jalang juo, nak tapakai kapandaian, jan dibaok lalok tidua, usah dibao makan kanyang.
(Biar senang hati Buyung, cobalah berjalan hilir mudik, jangan takut berberas bakar, walau jauh jelang juga, biar terpakai kepandaian, jangan di bawa tidur, jangan dibawa makan kenyang)
Jan bak cando urang kini, gilo deta jo saluak sajo, awak pangulu janyo urang, malah urang mahimbau datuak, kuduak angek hatilah gadang, labu jo kundua tak babeso, indak tahu dicupak gantang, indak tahu di adat limbago, hukum sarat jauah sakali, kalau lai bana baguru, nak pandai sabatang rokok, nak malin sagalok dama.
(Jangan bagai orang sekarang, gila deta dengan saluak saja, kita penghulu bagi orang, malah orang memanggil datuk, kuduk panas hati besar, labu dengan kundur tak berbesa, tidak tahu dicipak gantang, tidak tahu ada lembaga, hokum sarat jauh sekali, kalau benar sudah berguru, biar pandai sebatang rokok, biar malin segelap damar).
(Data 34/RdL/AUMP, Hlm. 63. Prg.2)
Kata-kata yang bercetak tebal pada kutipan tersebut merupakan majas satire lokalitas Minangkabau. Hal itu ditandai oleh kata-kata Jan bak cando urang kini, gilo deta jo saluak sajo, awak pangulu janyo urang, malah urang mahimbau datuak, kuduak angek hatilah gadang, labu jo kundua tak babeso, indak tahu dicupak gantang, indak tahu di adat limbago, hukum sarat jauah sakali.
Sebagaimana yang diketahui, satire lokalitas Minangkabau mengacu kepada uraian kata-kata yang harus ditafsirkan lain dari makna permukaannya sehingga diketahui maksud pengungkapan yang bertujuan untuk menertawakan atau menolak sesuatu dan sekaligus khas Minangkabau. Kata-kata jan bak cando urang kini, gilo deta jo saluak sajo merupakan sindiran terhadap pemimpin pada suatu kaum, tetapi tidak memiliki kompetensi dan tidak peduli dengan kondisi kaumnya sehingga orang tersebut dikatakan indak tahu dicupak gantang (tidak tahu dengan cupak dan gantang), indak tahu di adat limbago (tidak tahu adat dan lembaga), hukum sarat jauah sakali (hukum syara’ jauh sekali).
Kata-kata ini mengisyaratkan sebagai nasihat oleh seorang ibu kepada anak lelakinya (Rancak di Labuah) agar ketika anaknya menjadi pemimpin kaum nantinya ia tidak menjadi orang yang tidak berilmu. Jika hal itu dilakukan, konsekuensi ini akan berdampak terhadap nama baiknya secara pribadi dan kaum. Oleh sebab itu, untuk membentengi hal semacam ini agar tidak terjadi, bentuk sindiran lainnya dapat dicermati pada kutipan berikut ini.
Manolah anak kanduang denai, dangakan bana denai katokan, sakali kato urang lalu, jan takuik nyawo ka tabang, jan ganta darah kan taserak, jan malu dibaok pulang, baitu adat anak laki-laki. Baiak mandeh katokan juo, jikok malu dibaok pulang, kito bacarai kini nangko, usah dipijak halaman denai, usah ditingkek janjang denai, jan ditapiak rumah nangko, itulah nan pitaruah mandeh, pacik ganggam arek-arek.
(Manalah anak kandungku, dengarkan benar yang ibu katakan, sekali kata orang berlalu, jangan takut nyawa akan terbang, jangan gentar darah akan tertumpah, jangan malu dibawa pulang, begitu adat anak laki-laki. Baik ibu katakan juga, jika malu dibawa pulang, kita bercerai sekarang ini, jangan dipijak halaman rumah, jangan ditingkat jenjang ibu, jangan ditepik rumah ini, itulah yang ibu pesankan, pegang genggam erat-erat).
(Data 6/AnT/GIK, Hlm.20)
Kata-kata, seperti jikok malu dibaok pulang, kito bacarai kini nangko, usah dipijak halaman denai, usah ditingkek janjang denai, jan ditapiak rumah nangko juga merupakan bentuk sindiran terhadap anak yang tidak berkarakter; tidak sebagaimana anak lelaki yang ideal di Minangkabau. Dalam mamangan di Minangkabau dikatakan kok tanah sabingkah alah bamiliak, kok rumpuik salai alah bapunyo, malu nan alun babagi (jika tanah sebongkah telah bermilik, rumput sehelai telah berpunya, malu yang tidak dapat dibagi).
Dari hal itu, menurut alam pikiran orang Minangkabau secara ideal, merendahkan harga diri merupakan suatu keaiban. Rasa malu itu akan melibatkan seluruh kerabat dan lingkungan masyarakatnya sendiri karena perbuatan itu dapat mencemarkan nama baik keluarga atau lingkungannya.
Jatuhnya harga diri seorang anak karena tidak pandai menjaga malu, seolah-olah mereka, keluarga si anak, tidak mampu mendidik atau menunjukajarkan keturunannya dengan karakter yang kuat serta dianggap seolah-olah mengabaikan sistem hidup yang selama ini mereka muliakan.Untuk menutup rasa malu dalam menjaga harga diri, orang Minangkabau mengajarkan anaknya agar mampu memikul risiko dan konsekuensi yang dihadapinya.
Sebagaimana yang diungkapkan dalam mamangan, kaki tadorong inai padahannyo, muluik tadorong ameh padahannyo (kaki terdorong inan tantangannya, mulut terdorong emas tantangannya). Artinya, segala sesuatu yang dapat merugikan dan menjatuhkan harga diri kaum atau diri sendiri hendaklah ditebus atau bertanggung jawab penuh agar memberi malu keluarga atau kaum sehingga dalam mamangan dikatakan hiduik baraka mati bakiro (hidup berakal, mati berkira).
Andai kata rasa malu itu datang karena harga diri dijatuhkan orang lain, dalam petuah dikatakan, musuah indak dicari, basuo pantang diilakkan, tabujua lalu, tabilantang patah (musuh tidak dicari, bertemu pantang dielakkan, terbujurlalu, terlintang patah). Berkelahi bagi anak lelaki tidak dilarang. Namun, berkelahi yang dimaksud bukan untuk merusak, melainkan untuk mempertahankan harga diri dan diri dari serangan. (*)