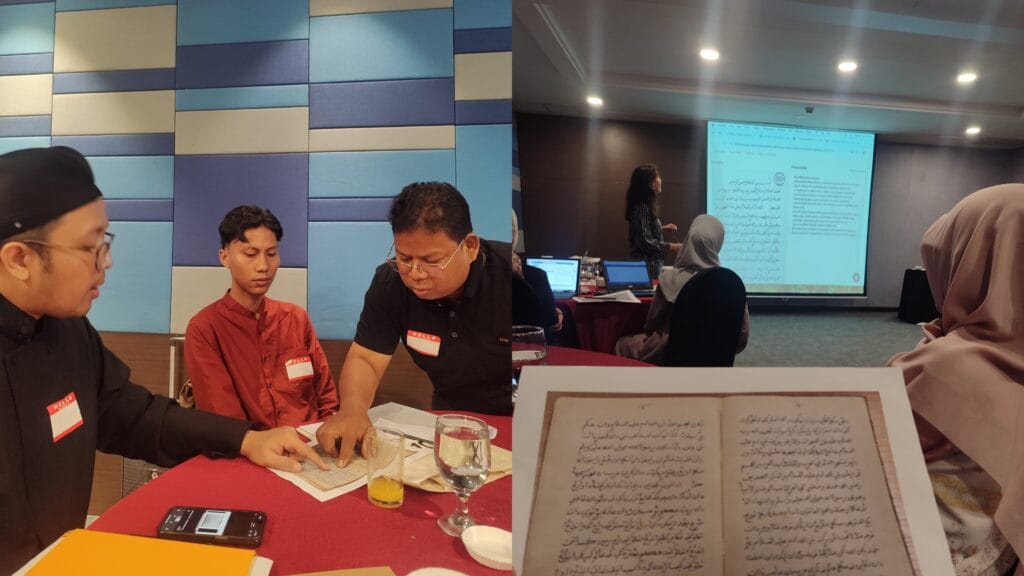Ada yang bertanya, kenapa Aceh dapat dua komunitas? Ini memang sekaitan dengan program Penguatan Komunitas Sastra Kementerian Kebudayaan RI. Bukan, bukan karena ada isu daerah paling ujung atau sekadar pengobat luka peristiwa berdarah GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Namun, karena memang ada rencana mendatangkan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Kalau cuma sekali kegiatan, juga mubazir.
Kemudian, niat mengadakan festival sastra berkapisitas nasional bahkan internasional perlu dirintis. Hikayat jadi kata kunci. Dan itu masih terdengar sunyi dalam gegap gempita sastra nasional.
Sophie’s Sunset Library dan Komplotan Bandit Warung Kopi masuk dalam daftar. Awalnya gelaran disepakati 11 dan 12 September. Namun, masalah administrasi membuat Komplotan Bandit mengundurkan acara. Jadilah, saya menapaki Banda Aceh jelang pergantian hari di dua tanggal itu.
***
Lagi, ini adalah perjalanan pertama. Butuh teman sebagai pemandu. Saya kontak Mirzan. Teman sewaktu 21 hari dalam proses Tendik Karao Volkano bersama Teater Rumah Mata Medan. “Saya di Aceh Barat, Bang. Baru balek,” infonya.
Untung masih ada T. Zulfajri. Tejo, panggilannya. Anggota Perkumpulan Nasional Teater Indonesia (Penastri). Bukan karena saya wakil ketua, tapi karena sudah bertemu di Djakarta Internasional Teater Platform (DITP) sebulan sebelumnya.
Masuk kamar sudah larut malam. Saya info Tejo untuk bertemu besok saja. Ia datang usai Jumat. Langsung bawa makan. Mau bayar, tapi dompet tinggal dalam tas di mobil. Tejo ambil alih. “Aman, Bang” ujarnya singkat.
Ke Sophie’s Library, 13 km dari hotel. Sepanjang jalan, tentu saya membayangkan Aceh. Atau pernah bernama Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh yang kita kenal dari berita dan sejarah: kaya budaya, teguh dalam syariat, dan penuh daya tahan. Atau Aceh yang lebih sunyi dan jarang disorot, adalah realita bahwa masyarakat—terutama di kantong-kantong pedalaman atau pinggiran—seringkali tidak mendapatkan akses yang setara dengan daerah lain di Indonesia. Khususnya, dalam konteks pendidikan, literasi, dan ruang-ruang publik yang inspiratif.
Kesenjangan akses ini, ironisnya, kadang-kadang menjadi api yang membakar semangat para pegiat lokal. Mereka muncul sebagai mercusuar yang dibangun dengan keringat dan idealisme.

Kami membelah jalanan Aceh Besar menuju Lhoknga. Begitu kami tiba di Pantai Kuala Cut, pemandangan itu memukul mata dan hati secara bersamaan. Terletak tepat di tepi pantai, dengan pasir putih dan deru ombak sebagai backsound abadi, berdirilah Sophie’s Sunset Library.
Ini bukan sekadar perpustakaan, ini adalah laboratorium literasi, dan rumah harapan yang dibingkai oleh senja paling dramatis. Sayang, kami tak mendapatkannya hari itu. “Belum bulannya,” info Nur Raihan, si pemilik tempat. Mestinya, matahari jatuh disebelah kanan apabila menghadap laut. Karena persoalan angin, awan terlalu banyak menutupinya. “Akhir Oktober lah,” tambah Kak Nur.
Ratusan buku tertata rapi di rak-rak, berdampingan dengan pernak-pernik seni yang dibuat dari barang bekas. Saya yakin, tidak ada tempat baca seindah ini di Indonesia.
Di tempat lain, perpustakaan sering kali terkurung dalam gedung kaku dan berpendingin udara, terpisah dari denyut kehidupan. Tapi di sini, literasi dan kehidupan menyatu. Anda bisa membaca puisi sambil merasakan angin laut, atau membahas filsafat ditemani aroma garam dan deburan ombak.
Paya Nie Karya Ida Fitri dibahas. Raisa Kamila jadi narasumber. Bintang tengah bersinar dalam kepenulisan Aceh. Sekolah di Leiden, mendalami filsafat, membuat perbincangannya runut.
Karya yang Juara 3 Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2023 dan masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award 2025 ini melihat peristiwa GAM dari sutu pandang perempuan. Paya itu rawa payau. Seperti Payakumbuh. Tempat mengumpulkan purun untuk jadi tikar. Berkisar pada empat perempuan penyuplai makanan pada Tentara GAM.

“Tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini memiliki karakteristik yang kuat, tangguh, dan berani mengambil risiko. Mereka merasa mempunyai tanggung jawab untuk merawat kehidupan, dan itu karakteristik khas perempuan Aceh. Ketika konflik, karakteristik itu terlihat sangat tebal, dan setelah konflik usai hal tersebut tetap ada,” tutur Raisa.
Menurut Raisa, tema luka sejarah sebelumnya, memang selalu dilihat dari sudut laki-laki. Sampai ia bilang, laki-laki membutuhkan perang untuk merasakan sakit yang dialami perempuan; melahirkan atau datang bulan. Karena itu, novel ini jadi penting, tersebab perempuan ikut menjadi bagian penting dalam perawatan perdamaian di Aceh.
Soal Paya pun disorotinya. Baginya, itu latar baru dalam lanskap bercerita di Aceh. “… biasanya setting-nya selalu tentang kota, desa, gunung. Rawa sendiri bagi orang Aceh adalah lanskap yang sangat dekat karena seperti Banda Aceh, juga kota dengan banyak rawa,” tambahnya.

Diskusi sore itu sangat ramai. “Bahkan diskusi paling ramai yang pernah diadakan di Sophie’s” ujar Kak Nur saat memberi sambutan. Kemudian, Fuadi S Klayu, seniman tradisi, tampil membawakan hikayat. Ia menciptakan pantun saat itu. Sama dengan tukang rebab. Suaranya khas dendang Aceh; punya nada dasar tinggi dan berdengung indah di ujungnya. Banyak pantunnya bercerita tentang pentingnya dan mengajak menyemarakkan literasi.
Usai acara, seperti halnya di Pontianak, saya menawarkan agar komunitas di Aceh bisa mengajukan kegiatan festival untuk tahun depan. Hikayat mungkin bisa menjadi pembeda paling signifikan dengan daerah lain.
“Oke,” kata Kak Nur.

Raisa juga menanyakan bagaimana menambah jejaring. Saya bilang, UWRF sedang membuka diri untuk kerja sama program. “PPF (Payakumbuh Poetry Festival) mendapat satu program dari penyair Lebanon,” info saya.
“Ah, ini gunanya bertemu dan berjejaring,” ucap Raisa.
Malamnya, saya diajak Tejo singgah ke markas Teater Rongsokan. Beberapa orang sudah menanti. Kami banyak bercerita tentang suasana kesenimanan Aceh. Dari dulu, sebenarnya saya memahami keadaan. Keadaan yang sebenarnya terjadi di seluruh koloni kesenian di Indonesia.
Teman-teman Tejo yang saya kenal sepintas itu, tertawa sinis, ketika saya sodorkan nama-nama seniman yang punya potensi pulang kampung dan membangun kesenian lebih baik. Mereka menceritakan sebabnya kenapa seniman itu tidak mau menetap di Aceh. Giliran saya tertawa keras. Sangat keras.

***
Saya tak langsung kembali ke Padang esoknya, meski jatah dari kementerian sudah habis. Bertahun lalu, Ayah Saya mendirikan surau di Pidie. Efek gempa. Semua mata ke Banda Aceh. namun, beberapa wilayah yang hanya terkena gempa dan kerusakan dianggap tidak seberapa, luput.
Tejo mencarikan mobil dan sopir. Pagi pukul Sembilan, Fahmi menghubungi. Kami bertemu di lobi hotel.
Perjalanan ke Pidie empat jam. Separonya saya habiskan untuk tidur. Separonya lagi, berbincang dengan Fahmi. Ia yang melepas nafas terakhir ibu, dalam rengkuhannya, saat diterjang tsunami. Memori itu membuatnya oleng secara psikologi. Untung, ada keluarga angkat yang menyelamatkan hidupnya.
kami sampai jelang makan siang. Ayah meminta saya menghubungi pengurus masjid. Namun, saya tidak mau. Hanya we a dan tak mengacuhkan apakah dibalas atau tidak. Seperti yang saya duga, surau itu kurang terawat. Setelah difoto, solat, lalu makan siang. Fahmi tak bertanya apa-apa. Meski dua pemuda yang datang menyaksikan kegiatan, ingin sekali tahu, kami sedang apa.
Pada Fahmi, saya bilang mau ke Makam Syekh Abdurrauf As-Singkili. “Kita masuk tol, Bang. Agar sampai tepat waktu,” tawarnya. Saya mengangguk.

Sebagai ‘fans garis keras’ Syekh Burhanuddin, tentu tak akan melewati makam gurunya. Ketika di googling, ada dua kuburannya. Satu di Banda, satu lagi di Singkil. Ke Singkil sungguh mustahil. Yang di Banda Aceh kemudian jadi tujuan. Yang ditetapkan MUI Aceh. Muridnya lebih ramai kontroversinya di Ulakan. Hingga hari ini.
Sampai di lokasi, saya termangu. Tak kalah terawatnya tempat itu dibanding lokasi Sykeh Burhanuddin. Bahkan untuk masuk ke sana melewati beberpa tempat. Syarat biasa ditetapkan, mesti berwuduk terlebih dahulu. Di dalam makam juga tak boleh berfoto. Ada seorang lagi sedang zikir ketika saya masuk.
Saya lebih tertarik makam sekitarnya. Sewaktu ke Palu, ke Makam Datuk di Bandang, hampir seluas ini. Ada juga makam yang bersanding dengan makam utama. Namun, yang Syiah Kuala ini lebih banyak.
***
Karena datang pada malam hari, saya tak begitu memperhatikan Bandara Udara Sultan Iskandar Muda. Jadi, dengan mental tergesa, saya mendatanginya pukul 11. Fahmi tak memberitahu bahwa tidak banyak penerbangan dari dan ke Banda.
Saya tertegun. Bandara itu lengang. Ini bandara internasional, kata saya dalam hati. Pesawat saya baru akan datang pukul 1 siang. Ada seorang bapak bersandar di sebuah kursi. Di belakangnya kedai kopi. Bisa dihitung jari warung modern.
Ia terkantuk. Menyandarkan kepala ke belakang. Saya ‘tertular. Akhirnya, memilih tidur di bangku kosong. Dan benar, tertidur. (*)
Eksplorasi konten lain dari Cagak.ID
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.