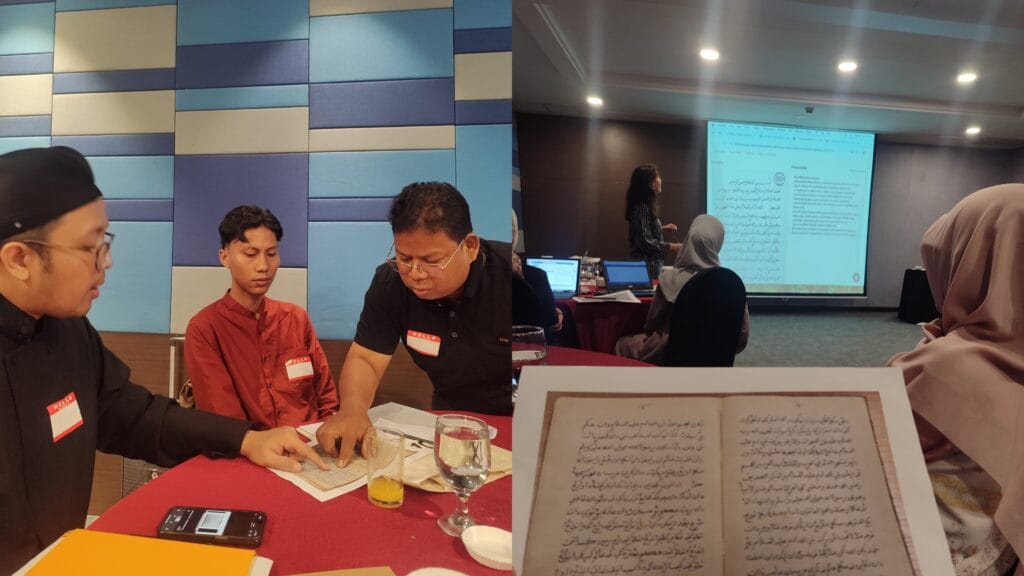Ladang saya yang tidak begitu luas itu, kalau hasilnya baik, akan menghasilkan panen yang lumayan juga. Selama pandemi melanda, saya jarang datang ke kampus. Saya telah memperluas lahan garapan dan lebih banyak menghabiskan hari di ladang. Hasilnya saya jual ke pasar, sejauh ini, dengan cara saya titip saja ke orang kampung yang pergi ke pasar. Tanggung saja membawanya sendiri ke pasar. Tapi suatu kali saya beranikan diri untuk menjualnya sendiri. “Cobalah jual sendiri, lain pula nikmatnya ketika menerima uang di tangan dari hasil kerja mengolah ladang, seberapa pun kecilnya,” kata seseorang.
Akhirnya saya pergilah memberanikan diri membawa hasil panen dari ladang saya itu ke Pasar Padangluar. Berjarak sekitar 10 kilometer, kira-kira 20 menit berkendara dengan sepeda motor dari tempat saya tinggal, atau sekitar 4 kilometer dari pusat kota Bukittinggi. Pasar itu pasar penampung terbesar untuk berbagai jenis sayur di seluruh dataran tinggi Minangkabau, Sumatra Barat. Pasar itu beroperasi setiap hari kecuali hari Senin. Selain pasar tersebut, sebenarnya ada 3-4 pasar lain yang menampung sayur dari berbagai sentra penghasil sayur di sekitar gunung-gunung besar di pusat Minangkabau, hanya saja pasar-pasar lain itu tidak buka setiap hari seperti pasar yang sedang saya tuju.
Saya sudah sering juga mendatangi pasar itu untuk berbelanja bahan dapur, atau sekadar menemani istri membeli sesuatu. Tetapi mendatangi pasar itu untuk menjual hasil panen dari ladang sendiri sejauh ini belum pernah. Jadi sekali itu saya mencoba naik angkutan desa (angdes) ke pasar itu. Membawa sekarung kecil cabai rawit. Ketika saya naik, mobil yang saya tumpangi masihlah kosong, yang karena itu saya merasa nyaman juga berada di atasnya, sekalipun kain jok pada bangku-bangku panjang mobil itu sudah bersemburan di sana-sini. Saya buka jendelanya lebar-lebar untuk membiarkan angin pegunungan yang sejuk dan lembut menerobos masuk. Tetapi, tidak berapa lama berjalan, mobil itu sudah mulai diisi penumpang lain oleh penumpang lain yang nyaris semuanya ialah petani yang akan menjual hasil panenannya ke pasar yang sama dengan saya. Semakin lama berjalan, mobil itu semakin padat, dimuati sebanyak mungkin barang yang bisa dimuat. Jadilah saya tersudut disesaki barang-barang itu. Pada atap mobil itu lebih banyak lagi barang-barang yang ditumpuk di situ, berkarung-karung hasil panen, yang diikat dengan tali, yang ikatannya menjuntai-juntai pada jendela yang terbuka yang sesekali mengenai kepala saya. Penumpangnya nyaris semuanya perempuan. Jarang laki-laki yang menumpang angkutan desa. Kalaupun ada, hanya laki-laki yang tidak pandai mengendarai motor, sudah tua lantas dilarang anaknya berkendara sendiri, atau karena memang tidak punya motor untuk dikendarai, yang kemudian memilih menaiki angdes ke pasar untuk menjual hasil panen. Ketika itu, malangnya, sayalah sendiri penumpangnya yang laki-laki.

“Bawa apa, Pak?” tanya seorang perempuan setengah baya tepat di depan saya. Tubuhnya agak bonsor. Di pangkuannya terdapat sekantong merah besar salada.
“Nih, cabai rawit, sekarung kecil,” kata saya.
Dia tambah bertanya, “Mau-maunya naik angdes. Motornya rusak, Pak?”
Saya harus jawab apa. “Ingin mencoba saja,” kata saya akhirnya sekenanya.
Dia tersenyum senjang ke arah saya. Katanya lagi, anak perempuannya kuliah di universitas tempat saya mengajar. Dia menyebutkan namanya. Saya coba mengingat-ingat, tidak teringat.
“Mahasiswa di kampus kan banyak ya Pak, mana mungkin akan ingat semua,” katanya akhirnya, mungkin untuk menghibur dirinya sendiri, kalau betapa tidak dikenalnya anak perempuannya.
Mobil itu berbelok di jalan yang bukan jalurnya. Kali ini sampai jauh ke pinggir gunung, menjemput seorang penumpangnya yang sebentar tadi menelpon. “Jauh itu. Berapa banyak?” begitu saya dengan supir angdes itu berbicara di telpon genggamnya. Mungkin karena jumlahnya menggiurkan, si supir menyanggupi, mengelokkan tajam kendaraannya. “Sebentar ya Ibu-Ibu,” katanya kepada para penumpangnya di belakang. Setengah penumpang menghela napas agak panjang. Saya sudah lebih sejak tadi berulangkali menghela napas. “Mau diletakkan di mana lagi ini, sudah sesak begini?” kata seorang penumpang menggerutu. Tak ada jawaban dari si supir. Mesin mobilnya saja yang terdengar semakin keras menderu karena sedang menaiki pinggang pendakian tajam. Untuk sampai benar-benar penuh, angdes itu singgah ke sana-sini dulu sepanjang jalan kampung untuk mencari muatan. Sampai akhirnya, dengan muatan sesak seolah terhuyung, barulah mobil itu melaju keluar jalan kampung menuju jalan raya. Saya pasrah, kuyu di sudut, terjepit di antara penumpang lain dan berkarung-karung sayuran. Sedikit agak pening dan mual juga. Tapi mau apa. Betapa repotnya kalau saya memilih turun di tengah perjalanan.
Dulu, ketika sekolah di kota, saya sering naik angkot. Bahkan sebelum bisa punya kendaraan sendiri, ke mana-mana selalu naik angkot. Tetapi, naik angdes muatan sayur padat-sesak begini barulah kali ini.

Setengah kilometer menjelang pasar, angdes kami sudah terjebak macet parah pula. Pengemudinya telah berusaha menyalib ke kiri jalan, melewati dua-tiga mobil, sampai akhirnya tertahan truk tangki besar milk Pertamina. Klaksonnya menggema kencang ketika tiba-tiba saja sebuah sepeda motor penuh muatan sekarung besar sayur memotong jalurnya di tengah lalu lintas padat jalan raya itu. Ketopoh suara knalpot truk-truk besar lain, teriakan-teriakan supir angdes, deru mesin ojek motor dan mobil-mobil minibus sewaan, berdesak-desakan menyesak dan mendesak di kedua sisi jalan. Ketika akhirnya angdes kami sampai di pertigaan menuju ke dalam pasar, kuli-kuli angkut dengan gerobak dorong mereka tampak sudah mengantre di pintu angdes, menyongsong angdes yang belum sepenuhnya berhenti. Beberapa kuli yang lain mengandalkan kekuatan pikulan belaka, kadang mereka bertelanjang dada, menonjolkan otot-otot legam yang liat. Ketika seorang di antaranya menaikkan barang ke pikulannya dengan semacam pengait khusus dari besi, mukanya tampak meringis menahan berat; karung-karung besar yang sarat berisi segala macam komoditas pertanian seperti cabai, bawang, sawi, waortel, kentang, jagung, ubi jalar, tomat hingga bunga kol tentulah memang berat.
Saya tidak perlu mengupah kuli-pikul untuk barang yang saya bawa. Saya tinggal menjinjingnya belaka. Hanya mereka yang membawa karung-karung besar saja yang mau tidak mau mengupah kuli-kuli pikul.
Setelah menyeberangi kemacetan parah itu, saya memasuki gerbang pasar. Selagi masih di pinggir jalan, saya sudah disambut beberapa pedagang yang mencoba menawar apa yang saya bawa. “Apa yang dibawa? Cabai ya? Sinilah, sinilah, langsung timbang!” Seorang perempuan setengah baya menggiring saya ke arah timbangan miliknya pada pinggir trotoar setengah lapuk dan berantakan. Seorang lain menyoraki saya dari arah dalam pasar, “Cepatlah, cepatlah, mobil [truk] mau berangkat!” Sembari mendekat dan memegangi karung saya, “Berapa mau dijual ini?”
Saya shock juga awalnya, merasa setengah ‘diteror’. Tetapi, untungnya, sebelum membawa panenan saya ke pasar, saya sudah dinasihati, “Jangan jual ke pakang, cari saja Si Anu, gudangnya di sisi mudik dekat simpang terminal, sebut saja itu cabai punya saya!” Berdasarkan nasihat itu, kepada ‘peneror’ itu, saya bilang saja dengan agak ketus, “Sudah langganan dengan Si Anu!”
Harga cabai merah keriting memang sedang naik. Harganya lagi bagus sekali malah. Jadi, apa pun jenis cabainya, ikut terbawa naik. Termasuk cabai rawit yang saya bawa. Apalagi, jarang petani yang mau menanam cabai rawit. Lebih tahan hama memang. Tidak susah betul merawatnya. Sekali-sekali saja diracun. Pupuk kandang saja cukup. Usia hidupnya juga lebih panjang. Tapi mengambilnya yang susah. Kalaupun mau diupah orang untuk memetik, satu orang paling banyak hanya bisa memperoleh hasil paling banter 7 sampai 8 kg saja sehari. Itu sebabnya, itu tanaman untuk orang-orang tua yang berladang untuk tidak menghasilkan uang banyak. Sekadar mengisi hari-hari menjelang mati. Mereka dengan kesabaran tinggi. Makanya, jika ada yang membawa cabai rawit ke pasar, jika harga cabai keriting lagi mahal, maka para peminat cabai rawit juga akan banyak. Cabai rawai bisa jadi penambah atas kekurangan rasa pedas akibat cabai biasa yang mahal. Makanya, para pedagang perantara itu mau saling berebut untuk mendapatkannya.

Tetapi, Anda tahu, para pedagang perantara itu, yang disebut pakang, mereka lihai menekan harga. Mereka bisa saja mengambil harga lebih tinggi dari harga yang dipatok pengumpul besar, tetapi kalau nanti harga sedang murah, mereka jadi cenderung melengahkan saja setiap tawaran dari petani dengan tidak mau membeli. “Sudah banyak, sudah banyak, tidak membeli lagi!” biasanya begitu mereka berkata. Untuk itulah para petani lebih suka berlangganan dengan pengumpul-nya masing-masing, pengumpul besar yang punya gudangnya sendiri di pasar itu. Mau harga tinggi ataupun murah, pengumpul langganan akan bersedia menampung berapa pun jumlah panenan. Pengumpul langganan kadang sudah seperti ‘juragan’. Tidak jarang, petani bisa mengutang segala di pengumpul langganannya, dibayar ketika masa panen tiba. Bisa juga, setiap panen diantarkan, duitnya tidak diambil dulu, tapi didepositokan saja di sana, nanti kalau sudah beberapa kali baru diminta dalam jumlah yang relatif banyak. “Lebih terasa besarnya uang yang didapat dengan cara begitu,” kata seseorang kepada saya yang sedang menjual ke ‘juragan’ yang sama ketika saya tanyakan tentang itu.
Juragan, atau touke, pemilik gudang besar di tengah pasar tempat saya menjual hasil panen saya itu bertubuh gempal, dengan bekas luka terbakar panjang menjalari tangan kirinya, mukanya penuh jejak-jejak–semacam–penyakit cacar di masa lalu. Dia duduk di belakang meja kecilnya nun di sudut ujung gudangnya, dengan kartu-kartu nama memenuhi kaca yang melapisi bagian atas meja. Dengan sedikit isyarat tangan darinya, dia memerintahkan seorang pesuruhnya menaikkan cabai rawit yang saya bawa ke atas timbangan yang terletak di depan gudang. Saya diminta mengikuti, untuk menyaksikan gerakan jarum pada angka timbangan. Setelah jarum berhenti pada angka tertentu, mata pesuruh itu memelototi saya sejenak. Saya mengangguk, tanda setuju. Dipotong berat kotor. Hasil bersihnya lalu dikalikan harga jual ketika itu, saat itu, sebab harga bisa saja berubah, di waktu yang berbeda, bahkan di hari itu juga, jika seandainya datang telepon dari Pekanbaru atau Jambi, Batam atau Palembang, Medan atau Jakarta, atau dari mana pun yang ke sana komoditas-komoditas yang telah dikumpulkannya itu akan dikirim. Jika permintaan di sana naik, harga akan naik juga di sini, begitu juga sebaliknya. Lalu, setengah berteriak, pesuruh itu mengatakan ke juragannya, hasil penimbangan, dan berapa total yang harus dibayar. Lalu, juga dengan sedikit isyarat tangan ke arah saya, dia meminta saya menuju ke arah juragannya. Dari tas sampingnya, touke itu mengeluarkan dan menghitung uang lembaran-lembaran besar, lantas menyerahkan hasil penjualan ke tangan saya. Dari laci meja kecilnya, dia mengeluarkan recehan.
Saya akhirnya berhasil menjual cabai rawit yang saya bawa untuk pertama kali. Memang, ada perasaan aneh yang menjalari saya, yang sulit juga untuk digambarkan, ketika menerima uang hasil penjualan di tangan. Kepuasan dan kesenangan yang unik.
“Membeli jagung juga?” tanya saya.
“Berapa banyak?” tanyanya balik.
“Sekitar dua karung ayam,” kata saya mengira-ngira. Saya juga belum dapat memastikan berapa banyak jagung di ladang saya yang dapat dipanen.
“Bawa saja ke sini, tapi jangan besok, dua hari lagi!” Katanya, besok sudah ada petani lain yang akan menjual jagung kepadanya. Tidak besok juga, kata saya, paling agak seminggu lagi baru bisa dipanen. “Telpon dulu kalau mau membawanya ke sini, takutnya nanti bertumpuk barang.”
Saya menganguk, berterima kasih, dan berlalu.
Sekali, sehabis menjual hasil panen, saya duduk di kedai kopi yang ramai di dalam pasar. Persis di pertigaan yang padat di seberang terminal penampungan, di mana truk-truk besar berjejeran. Seluruh meja nyaris sudah terisi. Satu meja, dengan dua bangku kosong, mempersilakan saya duduk. “Di sini sajalah duduk, biar bisa mengobrol!” seseorang, bertubuh tinggi besar dan gelap, memberi tempat duduk untuk saya. Saya pesan makan dan minum. Soto dan teh telur. Dia dan beberapa temannya asyik mengobrol. Dari lengannya mengular tato, naga menyemburkan api. Setiap yang lewat di situ, menyapanya dengan panggilan ‘Ketua’.
Dia sedang masuk angin, wajahnya terlihat mumet, meringis, menahan perasaan tidak enak. Seorang lain datang, menguruti panggal lehernya dengan batu cincin. “Apa ini?” tanyanya. “Sapir!” Jawaban yang terdengar pongah. Seorang keling pemilik lapak rempah di dalam pasar baru saja menghadiahinya. Sang Ketua beberapa kali terdengar bersendawa. “Asam lambung,” kata temannya itu, sambil terus mengurutkan sapir miliknya ke pangkal leher Sang Ketua. “Iya, kalau terlambat sebentar saja makan, sudah langsung kumat,” balasnya.
“Saya ada ranitidin,” kata saya menawarkan. Sambil mengeluarkannya dari dalam saku jaket.
“Ampuh?”
“Bisa untuk menetralisir,” jawab saja sambil memberinya dua tablet.
“Saya foto saja, nanti saya beli di toko obat,” katanya berbasa-basi.
“Ambil saja, tak apa, saya masih banyak. Diminum setengah jam sebelum makan!”
Dia mengangguk.
Lalu tak berselang lama, sebuah mobil penuh muatan sayur lewat di depan kedai kopi itu. Teman Si Ketua itu beranjak dari kursinya, menyerahkan sebotol air mineral pada supir yang membayarnya dengan uang sepuluh ribuan. Semacam karcis masuk pasar. Bercakap-capak sebentar dengan supir itu.
“Membayar retribusi tak mau, mintak jalan [pasar] diaspal pula,” katanya menggerutu.
Jalan dalam pasar itu mungkin dulu berupa aspal yang baik, tetapi seiring pergantian waktu dan cuaca yang silih berganti serta sistem sanitasi yang buruk membuat genangan-genangan hujan tidak tertampung lagi dengan baik. Maka gambaran jalan-jalan di sana itu adalah jalan-jalan yang mengepulkan debu ketika panas dan tergenang oleh air berlumpur ketika hujan. Tenda-tenda warna-warni para pedagang yang menggelar lapaknya di depan petak-petak kedai semakin mendesak ke pinggir jalan itu. Aroma bawang prei, bawang merah, seledri, kol dan sawi, berbagai jenis cabai, dan lain sebagainya yang sedang dibersihkan di gudang-gudang penampungan sebelum di-packing untuk kemudian disusun dalam truk-truk besar, bercampur-baur dengan berbagai aroma lain: saluran pembuangan air yang mampet sehingga menguarkan bau busuk, aroma makanan dari lapak-lapak penjual makanan tak jauh dari situ, ditambah bau keringat para kuli angkut, supir-supir truk, serta petani-petani yang datang ke pasar itu membawa barang-barang produksi mereka, suatu kombinasi bau yang sangat menarik dan menggoda khas dunia ketiga yang berantakan.
“Apa pemerintah tak mau memperbaiki?” tanya saya memancingnya.

Pemerintah daerah mungkin sudah berulang kali mencoba menertibkan pasar itu. Termasuk jalan di depan pasar yang tidak pernah tidak macet, padahal sesungguhnya jalan itu begitu vital sebagai bagian dari jalur Lintas Tengah Sumatra. Ada rencana akan dibangun fly-over menanggulangi kemacetannya. Seorang calon anggota parlemen daerah, yang sedang begitu bersemangat, pernah bertemu dengan saya di sebuah restoran, berkata dengan yakin, “Kalau Ci terpilih, [penanggulangan] kemacetan di Pasar Padangluar, Pasar Kotobaru, atas pasar-pasar lain yang bikin mumet itu, akan jadi prioritas Ci.” Tapi, sampai saat ini, sekalipun telah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin, upaya semacam itu tampaknya gagal. Para pedagang tetap melimpah ke jalan raya. Tak ada yang mampu menertibkan tampaknya. “Pasar ini telah ada jauh sebelum negara ada,” kata seorang datuk (kepala suku). Petani yang membawa panen mereka, pedagang dalam segala tinggkatannya, para pengunjung biasa, mereka semua memenuhi tepi-tepi jalan dengan sayur sayur mereka, barang-barang mereka, perkakas-perkakas mereka. Ada juga rencana untuk menjadikan jalan di depan pasar itu menjadi jalan dua lapis yang besar, tapi tampaknya benar juga si datuk, “Negara sudah hadir lebih dulu dibanding pasar itu. Apa daya negara untuk mengubah tatanan yang sudah terbentuk jauh sebelumnya, sebelum pemerintahan dan negara ini ada?”
Tidak berselang lama, seorang lelaki tua dan cucunya, memasuki kedai kopi itu, terlihat mencari-cari kursi yang kosong dengan matanya sembari memesan sesuatu kepada pelayan. Mereka duduk di dekat saya.
“Apa yang dibawa, Pak?” tanya saja.
Katanya, dia membawa selada, satu kantong kecil. Hasilnya, cucunya dibelikannya raket bulutangkis. Merengek-rengek terus minta dibelikan. Lagi musim sekarang. Pergelaran Piala Thomas dan Uber memang sedang berlangsung di televisi.
Dia tampak membuka maskernya. Cucunya juga.
“Kenapa masih bermasker?” tanya saya lagi.
“Hanya jaga-jaga saja, daripada nanti kena razia,”katanya pula.
Pesanannya telah terhampar di meja. Dulu ada, orang kampungnya, membawa sawi sekarung penuh ke pasar, tanpa masker, kena razia polisi, hasil penjualan sawi habis untuk membayar denda. “Malah tekor!” katanya terkekeh. Ketupat sesuap demi sesuap masuk ke mulutnya. Kopi hitam dihirupnya juga. Cucunya asyik makan sendiri sambil sesekali membetulkan senar raketnya.
Asap rokok membubung memenuhi kedai kopi itu. Serombongan pengunjung lain terlihat di depan pintu kedai sedang berancang-ancang mau masuk. Sedang di luar kedai, pasar sayur itu terlihat makin sesak. Klakson menggema di mana-mana beradu dengan teriakan touke dan penjual yang sahut-bersahutan. Juga suara orang mengaji dari corong pengeras suara dari puncak atas mushalla pasar, deru mesin penggiling cabe dan pemarut kelapa, ketokan-ketokan pada lapak penjual alat-alat pertanian dan barang pecah belah. Kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang menguapkan hawa minyak pada udara yang semakin panas dan gerah.
Saya telah menemukan rasa betah yang aneh dengan duduk berlama-lama di kedai kopi di tengah pasar sayur yang pengap dan ramai itu. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang biasanya tidak saya temui dalam rutinitas saya, dan mengalami jenis obrolan yang berbeda sehingganya mengasyikkan. Tetapi, saya harus sadar diri, saya sudah selesai, dan ada pelanggan lain yang butuh tempat duduk, maka saya mesti bersiap-siap untuk angkat kaki dari kedai itu. Saya sudah harus balik, ke suasana kampung yang tenang, mengerjakan kerja rutin dari kampus yang selama pandemi dikerjakan dari rumah, atau di luar itu kembali bekerja di ladang saya yang sepetak kecil itu. Di pinggir jalan pasar, saya lantas menyetop angkutan desa menuju jalur pulang. Pintunya menepi persis di tempat saya berdiri. Saya longokan kepala saya ke dalamnya. Angdes itu penuh-sesak. Tidak ada bangku kosong tampak. Isinya, lagi-lagi, ibu-ibu semua, dengan buntalan-buntalan besar di masing-masing pangkuan, sementara di antara kaki-kaki mereka, pada lantai angdes, dimuati kantong-kantong plastik besar penuh terisi barang-barang belanjaan. “Masuk ke dalam Pak, terus saja ke dalam,” kata supir angdes itu menolehkan kepala ke belakang, “geser Bu, geser!” Tak ada seorang pun di antara penumpang yang mencoba menggeser duduknya, tak ada seorang pun yang berniat memberi saya tempat tampaknya, yang mungkin saja memang sudah tak ada tempat, sudah sepenuhnya penuh. Saya dilanda kebingungan, harus naik, atau menunggu angdes berikutnya datang? Sementara di belakang angdes itu, kemacetan semakin mengular, kendaraan-kendaraan lain bersahut nyinyir menekan klakson.
Saya akhirnya memilih naik. Pantat demi pantat saling bergeser, menyisakan celah sempit untuk saya duduk, di sudut terdekat, persis di belakang supir. Saya terjepit, lagi-lagi, di antara tubuh-tubuh, barang-barang, dan obrolan-obrolan ibu-ibu. Di tengah kemacetan, mobil kami terus merangsek maju. Perlahan-lahan, ingar-bingar pasar dan segala tetek-bengeknya, berlalu dan tertinggal. Tetapi, saya tahu, suasananya akan segera saya rindukan.
Pandai Sikek, 2022-2023.